
Oleh Naysilla – Pegiat Social Movement Institute (SMI)
“Rumah sakit rata-rata sudah tidak berorientasi sosial, tetapi justru dijadikan ladang bisnis di mana para pemilik modal berlomba- lomba membangunnya untuk mendapat keuntungan” (Eko Prasetyo – dalam buku ‘Orang Miskin Dilarang Sakit’)
Berita tentang kematian Raya, balita asal Sukabumi, kembali menampar kesadaran publik atas rapuhnya kondisi negara hari ini. Warga yang belum sepenuhnya pulih dari kemarahan atas kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati dan Bone kini harus dibuat geram atas luputnya peran negara dalam menjamin hak dasar warganya. Raya, seorang bocah yang meninggal karena penyakit cacingan dan TBC adalah fakta tragis yang seharusnya menjadi cermin besar negara.
Negara terbukti gagal menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Ayah Raya sakit-sakitan, ibunya seorang ODGJ, praktis membuat keduanya juga kesulitan untuk melayani diri sendiri, apalagi mengurus Raya. Kasus ini jelas bukan sekadar musibah pribadi, melainkan bukti nyata absennya negara dalam menjamin hak hidup dan kesehatan anak, hak yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.
Presiden Prabowo kerap berpidato, “Indonesia adalah bangsa yang besar!” Namun, nyatanya jaminan kesehatan sama sekali belum menjadi bukti kebesaran negara ini. Kebesaran macam apa yang bisa dibanggakan bila rakyat kecil masih kehilangan hak dasarnya atas akses pada layanan kesehatan? Meninggalnya Raya seharusnya jadi tamparan bagi para penguasa. Ungkapan duka dari pejabat nampaknya hanya basa-basi jika sistem kesehatan masih tidak dibenahi dan jauh dari jangkauan masyarakat miskin.
Reaksi Gubernur Jawa Barat yang menyalahkan kader posyandu dan gerakan PKK karena dianggap lambat serta tidak maksimal dalam melakukan penanganan juga keterlaluan. Para kader posyandu dan pegiat PKK bergerak dengan sukarela, tanpa bayaran, dan minim dukungan. Kader-kader ini mau bergerak sesederhana berlandas pada rasa peduli atas sesama warga. Sungguh sangat keterlaluan jika pejabat menyalahkan mereka atas dalih kelambanan. Menyalahkan mereka sama saja mengalihkan tanggung jawab negara ke pundak warga biasa.
Padahal, masalah sesungguhnya adalah ketimpangan struktural: sulitnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Masyarakat marjinal jauh dari kata merdeka atas pemenuhan hak kesehatannya. Negara ini betul-betul pincang jika terus membanggakan kemajuan infrastruktur, tetapi nyatanya tidak peduli pada kebutuhan warganya, bahkan di tingkatan paling dasar, yaitu kesehatan. Jika pemerintah hanya bangga pada pembangunan infrastruktur besar, tetapi gagal menyediakan layanan kesehatan dasar, itu menegaskan adanya prioritas yang salah dalam politik pembangunan.
Lebih ironis lagi, birokrasi juga menjadi benturan bagi pembiayaan kesehatan Raya. Tagihan perawatan Raya tidak bisa ditanggungkan negara karena ia tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Max Weber, pencipta konsep birokrasi, menekankan bahwa melalui birokrasi seharusnya membuat institusi dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, ketika negara membiarkan birokrasinya menjadi penghalang, birokrasi justru beroperasi sebagai mekanisme eksklusi yang menyingkirkan kelompok miskin dari akses layanan publik.
Melalui perspektif sosiologi, kematian Raya memperlihatkan wajah nyata kekerasan struktural. Johan Galtung menjelaskan bahwa ketika institusi gagal memenuhi kebutuhan dasar, penderitaan dan kematian yang muncul adalah produk dari struktur sosial itu sendiri. Maka, telah jelas, dalam kasus ini, nyawa seorang anak hilang karena absennya peran negara.
Tragedi ini juga mencerminkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai reproduksi ketidakadilan sosial. Anak dari keluarga miskin dan rentan lebih mungkin gagal mengakses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Kondisi orang tua Raya sejak awal menempatkan Raya dalam posisi subordinat dan negara bukannya memutus rantai kerentanan, melainkan justru membiarkannya berlanjut. Konstitusi yang menegaskan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” akhirnya hanya jadi kalimat hampa.
Kematian Raya seharusnya menjadi alarm nyaring bagi negara. Ia bukan sekadar kasus individual, melainkan bagian dari pola sistematis di mana rakyat kecil selalu jadi korban negara yang lebih sibuk membangun citra kebesaran daripada melindungi kehidupan warganya. Peristiwa ini menegaskan bahwa ketidakadilan tidak hanya soal kegagalan individu, tetapi hasil dari relasi kuasa yang timpang, birokrasi yang menyingkirkan, dan kebijakan yang abai pada kelas bawah.
Jelas, kematian Raya adalah peringatan keras: negara tak bisa lagi berlindung di balik retorika kebesaran. Ukuran nyata kebesaran sebuah bangsa adalah seberapa jauh ia mampu menjamin hak hidup warganya yang paling rentan dan di titik inilah, Indonesia (lagi-lagi) masih gagal. [red]
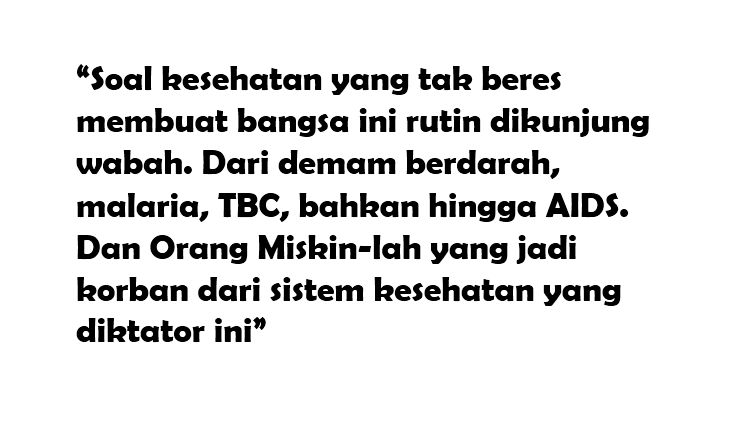
Kutipan dari buku “Orang Miskin Dilarang Sakit” karya Eko Prasetyo.